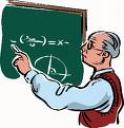 Dahulu, ketika B.J. Habibie masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi, banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang Habibie. Kenapa? Karena dia pintar, berilmu, bisa membuat kapal terbang, menjadi orang terkenal di Indonesia bahkan di dunia, bisa pergi melanglang buana ke berbagai negara dan lain-lain.
Dahulu, ketika B.J. Habibie masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi, banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang Habibie. Kenapa? Karena dia pintar, berilmu, bisa membuat kapal terbang, menjadi orang terkenal di Indonesia bahkan di dunia, bisa pergi melanglang buana ke berbagai negara dan lain-lain.
Siapa orangnya yang tidak mau menjadi orang pintar atau orang berilmu? Pasti, semua orang bakal menginginkannya. Dengan bekal ilmu dan kepintaran, minimnalnya orang bisa mengais rejeki sebagai modal hidup dengan mudah. Setiap orang tua pasti mempunyai cita-cita untuk menyekolahkan anaknya sebisa mungkin. Jangan sampai anaknya kelak menjadi orang bodoh, atau tidak tamat sekolah walaupun sekedar jenjang SD saja. Tak peduli, orang tua punya duit atau tidak. Pasti bakal mengusahakan mencari biaya untuk sekolah, walaupun dengan resiko ngutang sekalipun. Rata-rata kekhawatiran orang tua, mereka tak mau anaknya menjadi ‘sampah’ masyarakat. Mereka juga tidak mau, anaknya kelak bernasib seperti orang tuanya sendiri. Tidak mengenyam jenjang pendidikan, susah mencari kehidupan, tidak bisa baca tulis, tidak berwawasan dan lain-lain. ‘Jangan sampai nasib anak saya seperti bapaknya’, kata orang tua.
Sebegitu pentingnya pendidikan bagi manusia, negara pun turut bertangung jawab. Pendidikan menjadi hak asasi setiap warga negara. Dalam UUD ’45 Pasal 31 disebutkan;
(1)Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjungjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Negara menjamin pendidikan bagi setiap warganya dengan tujuan untuk memajukan peradaban bangsa dan menyejahterakan umat manusia. Trauma jaman penjajahan, mengusik para pendiri bangsa ini untuk bangkit dari kebodohan dan kemiskinan. Jangan sampai penjajahan fisik terulang kesekian kalinya untuk bangsa Indonesia. Indonesia dijajah karena bodoh dan miskin!
Nampaknya permasalahan tidak berhenti sampai di sini. Bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia dan menjadi kewajiban agama serta negara. Setelah puluhan tahun Indonesia terbebas dari penjajah, kondisi bangsa Indonesia sekarang tak jauh lebih baik ketika jaman dahulu.
Tahun 1950-an dan 1960-an, rakyat masuk sekolah di SR (Sekolah Rakyat) atau SMP tanpa dipungut biaya sedikitpun. Bahkan, segenap rakyat Indonesia waktu itu dirayu dengan susah payah bahkan dipaksa untuk mau ke sekolah, maklum tingkat orang Buta Huruf mencapai 90 persen. Iming-iming jatah segelas susu setiap pagi dari UNICEF dan pelayanan kesehatan bagi yang sakit menjadi fasilitas lebih. Padahal waktu itu, Indonesia baru saja lepas dari masa penjajahan.
Sekarang, jauh panggang dari api. Pendidikan menjadi hal yang tidak bisa disentuh oleh seluruh kalangan. Hanya orang berduit saja yang bisa menikmati pendidikan. Biaya pendidikan untuk masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi, mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Padahal kemerdekaan Indonesia sudah berumur 60 tahun. Kondisi perekonomian kita pun jauh lebih baik dibanding tahun 50-an dan 60-an.
Bahkan persentasi pengangguran, bukan sebatas orang-orang non berpendidikan saja atau berpendidikan setingkat SD. Lulusan dari Perguruan Tinggi menambah daftar antrean jumlah pengangguran di Indonesia. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Bukankah pendidikan di Indonesia untuk kesejahteraan umat manusia? Yang terjadi adalah untuk kesengsaraan umat manusia.
Justeru sukses pendidikan Indonesia, dikenal orang dengan label negatif. Indonesia masuk rangking teratas dalam urusan korupsi di Asia dan juga dunia. Menyedihkan memang! Padahal, -lagi-lagi menurut UUD-, pendidikan dimaksudkan untuk kemajuan peradaban bangsa. Yang terjadi adalah untuk keterpurukan peradaban bangsa. Moral dan harga diri bangsa jatuh dan menjadi cibiran orang lain.
Lantas bagaimanakah nasib penuntut ilmu? Haruskah kita terdiam diri, atau menjadi orang bodoh. Jelas itu bukan pilihan bijak. Untuk menentukan pilihan menjadi orang pintar pun, harus berpikir panjang. Lulusan sekolah atau kuliah pun, ternyata tidak lantas mendapat pekerjaan.
Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, “Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang paling pintar?”. Rasul menjawab; “Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya kamu bakal menjadi orang yang paling pintar”. Dari jawaban Nabi, ternyata ada perbedaan logika yang sangat mendasar dengan logika kebanyakan manusia.
Dalam pandangan Nabi, ada pesan khusus untuk menjadi orang pintar. Logika yang dipakai bukan standar manusia, tapi standar agama. Islam memberikan kunci sukses untuk menjadi orang pintar dengan bekal takwa. Islam sama sekali tidak melarang manusia untuk menjadi orang pintar (berilmu), bahkan sangat menganjurkan pemeluknya untuk mencari ilmu dari lahir sampai mati.
Takwa mengandung arti takut kepada Allah dan menjaga diri sendiri. Orang bertakwa hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada sesama manusia. Prinsip orang bertakwa adalah menggapai target kehidupan dunia (berarti: dekat) dan akhirat (berarti: jauh). Menggapai yang jauh, yang dekat pun pasti kesampaian. Orang bertakwa tahu akan target hidup, yaitu dunia dan akhirat. Bukan sebatas di dunia saja.
Karenanya kenapa orang bertakwa disebut orang paling pintar. Dia tahu bahwa hidupnya bukan sebatas di dunia saja, tapi juga di akhirat. Dia senantiasa berhati-hati dalam menjalankan segala kehidupannya dan menjaga jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang haram atau maksiat. Dia tahu dan sadar diri bahwa kelak kalkulasi segala amal perbuatannya bakal dihisab di akhirat. Sedikitpun tidak akan ada lolos dari hisaban Allah.
Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menghindar dari tiga tingkatan, sebagimana diungkapkan M. Quraish Shihab. Pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Kedua, berupaya melaksanakan perintah Allah sepanjang kemampuan yang dimiliki dan menjauhi larangan-Nya. Ketiga, dan yang tertinggi, adalah menghindar dari segala aktifitas yang menjauhkan pikiran dari Allah swt.
Mari kita menjadi orang bertakwa!
